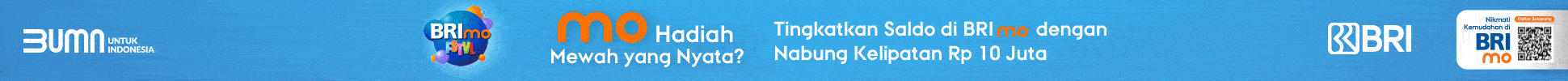Seluruh sejarah filsafat dibesut dari mitos.
Diracik oleh logos dan disempurnakan dengan mengaktifkan kemampuan berpikir kritis.
Secara garis besar logos merupakan makna harfiah dari kata, sabda atau firman.
Pasokan istilah Yunani ini pada abad awal masehi digunakan oleh Philo yang hidup di Alexandria (Mesir kuno) bersamaan dengan Yesus Almasih di Galilea sebagai perkamen Tora (Taurat) Yahudi dan kelak dimaknai sebagai “chekhoma” yang berarti hikmah.

Menurut kajian teologis gurubesar emeritis Olaf Schumann (85) dalam membahas hubungan kekristenan dan kebudayaan, istilah logos yang berpangkal dari aktivitas nous (harafiah: pikiran) dimaksudkan sebagai tradisi yang membentuk agama dan kebudayaan.
Agama bukan produk budaya. Sebagaimana budaya tidak pula memroduksi agama.
Jika agama diyakini untuk ditunaikan, itu tak membentuk suatu faset budaya.
Demikian sebaliknya, kompleksitas budaya bekerja dan bertugas dari realitas yang tak berurusan dengan soal-soal transenden.
Kebudayaan, setidaknya dalam rumusan Schumann, tak memiliki fasilitas logos dalam menjembatani praktek-praktek agama yang lebih berorientasi “ruhiyah” atau nubuwatan (prophetic).
Dengan kata lain, logos di dalam hubungan agama dan kebudayaan lebih ditandai sebagai reproduksi pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meretas misteri-misteri di balik pengetahuan logos itu sendiri.
Tak heran hampir semua sejarah pengetahuan dalam bingkai filsafat akan menjadi kata majemuk (plural verba) dengan semantik baru seperti bios-logos (biologi), psyche-logos (psychology), anthropos-logos (anthropology), sosio-logos (sociology), pathos-logos (pathology) hingga kriminal-logos (crimenology).
Dan akhirnya, ketika hendak menjemput maut di kamp Ausschwitch, dokter turunan Yahudi, Victor Frankl (1905-1997) — setelah selamat dari pembantaian holocaust Hitler — menulis kesaksiannya yang membuahkan ilmu “logotheuraphy” yang ditulisnya dalam buku terkenal dan laris: Man‘s Search for Meaning (From Death-Camp to Existensialism (1946).
Penulis: Reiner Emyot Ointoe (REO)
*) REO, fiksiwan yang memulai karirnya di bidang penulisan di media-media lokal hingga nasional. Telah melahirkan lebih dari dua puluh buku mengenai kebudayaan, sastra, sejarah dan profil tokoh.
Baca juga tulisan Reiner Ointoe lainnya:
- DIRGAHAYU MANADO (1830), “Manado is one of the prettiest in the East”
- Catatan REO: Ihwal Kematian
- 75 Tahun SARUNDAJANG: Persona, Pesona dan Sasmita