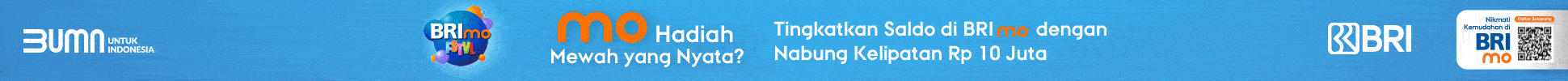Kawangkoan-Sekelompok pria paruh baya, dengan ikan kepala merah, berkumpul di bawah terik matahari. Sesekali mulut mereka komat-kamit sambil menengadah ke langit.
Salah seorang pria memakai baju khas Kabasaran -Tarian adat perang suku Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara- tampak sedang mengatur makanan di atas meja kayu sepanjang kurang lebih 3 meter.
Di atas meja kayu kemudian diletakan telur rebus, buah pinang, rokok, kower (mangkuk bambu) berisi kopi hitam, saguer (sejenis arak khas suku Minahasa, hasil fermentasi air dari pohon aren), masing-masing jumlahnya 81 buah yang merupakan jumlah dari Siou Maka Siou atau 9×9, angka keramat dari para leluhur atau juga jumlah saudara bersaudara dari para leluhur, dan sebuah Alkitab. Ada juga meja kayu terpisah, sepanjang 1 meter, ditelakkan 3 ekor kepala babi.
Di tanah dekat meja sesajian, disiapkan dua ekor babi hutan yang akan disembelih pada ritual nanti.
Sambil pria itu mengatur meja ‘sajian’, kelompok pria lainnya, terdiri dari 9 orang, menarikan tarian perang Kabasaran, lengkap dengan baju perang Minahasa, kain tenun berwarna merah, diiringi tambur.
Pada bagian kepala dari Sarian (pimpinan penari Kabasaran) ada mahkota yang dihias kepala tengkorak monyet dan bulu ayam jantan, pada penari lainnya ada juga yang diikat dengan tengkotak kepala burung Cendrawasi.
Ornamen lainnya di bagian tubuh ada Lei-lei (hiasan leher), wongkur (penutup betis kaki), di bagian kaki ada lonceng kecil atau giring-giring terbuat dari kuningan.
Pria yang mengatur meja, lagi-lagi memandang ke langit, cuaca masih cerah meski biasanya hujan deras. Namanya Herri Welang.
Hari itu, Kamis (15/12/2016), Herri tengah menyiapkan diri untuk memimpin ritual pemindahan 56 waruga Kina Angkoan di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.

Waruga merupakan kubur atau makam leluhur dari orang Minahasa yang bahan pembuatannya terbuat dari batu yang terdiri dari dua bagian, bagian atap dan bagian bawah. Pada bagian atapnya mirip atap rumah (bubungan), terdapat banyak pahatan dan hiasan seperti pahatan manusia, matahari hewan, tumbuhan dan lainnya.
Ada yang mengatakan bahwa hiasan-hiasan tersebut merupakan gambaran situasi saat orang yang ada di dalamnya mati.
Misalnya, ada yang meninggal waktu melahirkan, digambarkan dalam posisi mengangkang. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa hiasan-hiasan itu merupakan gambaran profesi saat orang itu masih hidup. Apabila di waruga tersebut ada gambar binatang, maka orang yang dikubur di dalamnya, dahulunya adalah seorang pemburu. Atau hiasan orang yang sedang bermusyawarah, maka dahulu orang yang dikuburkan di waruga itu adalah seorang hakim.
Pada bagian bawahnya berbentuk kotak yang bagian tengahnya ada ruang sebagai tempat meletakkan jenazah, dengan posisi jongkok, tangan memeluk kaki, mirip dengan posisi bayi sewaktu dalam kandungan.
Tanah tempat berdirinya waruga atau makan leluhur, kini akan dibangun mega proyek Bendungan Kuwil Kolongan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat.
Awalnya, masyarakat adat menolak pembangunan bendungan tersebut, namun setelah diadakan pertemuan antara lembaga adat desa, organisasi masyarakat adat, Pemerintah Desa Kawangkoan, Pemerintah Kecamatan Kalawat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Provinsi Sulut, Balai Pelestarian Nilai Budaya Suluttenggo, akhirnya dijelaskan tentang pentingnya pembangunan waduk untuk mengantisipasi banjir bandang di Kota Manado, sehingga disepakati pemindahan waruga.
Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu menggelar ritual pemindahan dengan ‘bae-bae’ (baik-baik).
MEMOHON RESTU LELUHUR
Sesajian di meja panjang sudah berjejer rapi. Dupa dipasang. Dua ekor babi hutan, mengerang saat diikat pada bambu. Kabasaran tetap menjalankan tugas mengusir pikiran jahat dari manusia, melalui tari-tarian adat.
Tim 9 yang dipercayakan melakukan ritual pemindahan ini terdiri dari lembaga adat Brigade Manguni, Paimpuluan Ne Tounsea serta lembaga adat ne Tounsea, dimana koordinator adalah Wani Unsulangi dan Yan Wurangian, unsur pemerintah dan perwakilan Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)-PT Daya Mulia Turangga (DMT) dan PT Nindya Karya, sudah berada di lokasi digelarnya ritual.


Sarian (pimpinan Kabasaran) Tonaas Ari Pantow, juga mendapat pertanda baik untuk menggelar ritual ini.
Ia menceritakan, beberapa tanda yang dia terima yaitu cuaca begitu cerah dan ada bunyi burung. “Sebelum keluar rumah harus berdoa, saya pamit kepada orang tua-tua (Dotu). Saya lihat langit begitu cerah padahal biasanya hujan deras. Ada juga bunyi burung, ini pertanda baik,” kata Sarian.
Tidak lama, kemudian masuk dua orang Pakempetan (mediator) yang memediasi dialog antara para leluhur dengan pemerintah.
Menurut Herry, sebelum hari ini, sudah dilakukan tiga upacara permohonan restu kepada leluhur.
“Pada upacara pertama sempat ditolak, kedua kemudian diterima, upacara ketiga menentukan jadwal pemindahan dan ini yang keempat. Setiap upacara, kami menggunakan Pakempetan,” katanya.
John Manopo selaku Tonaas-Gelar adat yang diberikan kepada orang-orang yang dapat menentukan di wilayah mana rumah-rumah itu dibangun untuk membentuk sebuah Wanua atau negeri dan mereka juga yang menjaga keamanan negeri maupun urusan berperang- segera membacakan doa, kemudian 40 personel tim Budaya Minaesaan Tombulu (di luar Tonaas dan 2 Pakempetan), menyembeli leher sepasang babi hutan, kemudian darahnya diambil dan dicelupkan ke tangan Pakempetan (mediator), yang nantinya lewat Pakempetan inilah terjadi komunikasi antar dua dunia berbeda, roh leluhur dan pemerintah.
Pakempetan lalu mengambil darah babi dengan kower (mangkuk bambu), lalu disiram ke lokasi pemindahan waruga yang sudah disiapkan, sekitar 30 meter jaraknya dari Kina Angkoan.
Saat kembali dekat meja sesajian, Jemmy Pangalila dan Daud Toreh yang menjadi Pakempetan mulai kemasukan roh leluhur.
Dibawah kendali leluhur, diperintahkan membuka Alkitab, Yeremia 10:1, yang menceritakan tentang Allah yang hidup dan berhala-berhala.
Pakempetan mulai menyampaikan pesan-pesan para Dotu (leluhur) dalam bahasa Tombulu dan bahasa Tonsea, baik dari Opo Toar dan Opo Makalew yang diterjemahkan Herry.
“Atur yang rapih, jangan terlalu berhimpitan, yang masih dikenali nama mereka diletakan bersama. Sedangkan yang tidak dikenali dikelompokan bersama. Bila ditemukan pusaka seperti keris, piring, kalung, gelang, cincin atau mustika, jangan berani ambil dengan maksud memiliki dengan tujuan tertentu. Sebab itu akan menjadi ‘senjata makan tuan’,” ujar para leluhur melalui Pakempetan Daud Toreh.
Ia melanjutkan, para leluhur sebenarnya sangat marah diminta makamnya direlokasi ke tempat lain, tapi karena yang meminta adalah keturunan Dotu, mereka pun siap dipindahkan.
“Dotu Opo Makalew mengatakan bahwa mereka ikhlas direlokasi, tapi cara pemindahannya harus sesuai struktur dan komposisi awal. Kalau posisi awal di sebelah kanan, maka di posisi baru juga harus sebelah kanan. Kalau pimpinannya di angkat dari posisi awal ada di depan dan anak buahnya di belakang, maka posisi relokasi juga harus sama seperti semula. Dengan begitu, akan dijauhkan dari malapetaka,” jelasnya.
Hal yang tak kalah menarik dan penting, Pakempetan sempat mengungkapkan bahwa leluhur dari Hukum Besar yaitu Gubernur Sulut Olly Dondokambey, terdapat juga di antara para leluhur yang ada di salah satu waruga Kina Angkoan.
“Kami sangat berterima kasih jika hukum besar ikut juga terlibat memikul dan memindahkan waruga. Karena leluhur hukum besar adalah salah satu leluhur yang ada di sini,” ujar Pakampetan.
Masih dalam penjelasan Herry, para leluhur meminta didirikan patung Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang merupakan keturunan langsung para leluhur Minahasa khususnya dari Tonsea.
“Dengan patung, akan dikenang generasi ke generasi leluhur Minahasa. Tapi Kabasaran juga dipesankan agar tidak hilang dari budaya Minahasa karena Kabasaran mampu mengusir pikiran jahat dari orang-orang,” ujarnya.
Setelah itu, para Dotu mengizinkan orang-orang untuk memakan sesajian, lalu para Dotu keluar dari tubuh Pakempetan (mediator).
Jemmy Pangalila dan Daud Toreh yang menjadi Pakempetan langsung duduk lesuh.
Herry bertindak cepat, berdoa untuk pemulihan Pakempetan. Sementara masyarakat yang hadir langsung berebut memakan sesajian yang dipercaya sebagai ‘obat’.


WISATA SEJARAH BUDAYA MINAHASA UTARA
Waruga merupakan salah satu peninggalan sejarah asli leluhur Minahasa, satu dari tiga suku terbesar di Provinsi Sulawesi Utara.
Waruga berdiri sejak zaman megalitikum atau zaman batu besar (sekitar abad ke-17) yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Berdirinya waruga sejak abad ke-17 dapat dibuktikan dari pahatan angka tahun pada beberapa waruga seperti: 1769, 1839, 1850 dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa Utara Dra Femmy Pangkerego MPd ME mengatakan, di Minahasa Utara terdapat kurang lebih 2000 waruga yang tersebar pada beberapa desa seperti Sawangan 142 buah, Airmadidi Bawah 155 buah, Kema 14 buah, Kaima 9 buah, Tanggari 14 buah, Woloan 19 buah, Tondano 40 buah, Kolongan 56 buah dan lainnya.
Ada beberapa versi mengenai asal usul nama waruga. Versi pertama mengatakan bahwa istilah “waruga” berasal dari kata “maruga” (bahasa Tombulu, Tondano, Tonsea) yang artinya “direbus”. Versi kedua mengatakan bahwa “waruga” berasal dari kata “meruga” (bahasa Minahasa Kuna) yang berarti “lembek” atau “cair”.
Sedangkan, versi yang lain menyebutkan bahwa “waruga” berasal dari dua kata, yaitu “waru” yang berarti “rumah” dan “ruga” yang berarti “badan”. Jadi, waruga dapat diartikan sebagai “rumah tempat badan yang akan kembali ke surga”.
Konon, waruga dahulu digunakan sebagai sarana pemakaman keluarga yang ditaruh di pekarangan atau di kolong rumah. Namun, tidak semua orang Minahasa Utara memiliki waruga. Hanya orang-orang yang mempunyai status sosial yang cukup tinggi saja yang memilikinya. Itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak.
Pada awal abad ke-20, tradisi mengubur mayat dalam waruga ini berhenti karena muncul wabah penyakit (kolera dan tifus) yang diduga bersumber dari mayat yang membusuk dalam waruga. Di daerah Sawangan, atas instruksi Hukum Tua (kepala desa), waruga-waruga yang tersebar di seluruh desa dikumpulkan dan di taruh di pinggir desa. Hal ini dilakukan agar warga desa tidak terjangkit wabah penyakit yang disebabkan oleh mayat yang membusuk tadi.
Waruga-waruga yang ada di daerah Minahasa ini mulai banyak menarik perhatian orang luar, terutama para peneliti, sejak CT Bertling menulis artikel De Minahasche Waruga en Hockernestattung yang dimuat dalam majalah Nederlansche Indis Oud en Niew (NION), No. XVI, tahun 1931. Setelah itu, CIJ Sluijk juga menulis artikel tentang waruga berjudul Tekeningen op Grafsten uit de Minahasa.
Pada tahun 1976, Drs Hadi Moeljono yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan, mengadakan penelitian tentang waruga di Kabupaten Minahasa.
Dari hasil penelitiannya itu, pada tahun 1977 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemugaran terhadap kompleks waruga di Sawangan dan Airmadidi.
Hasilnya, pada tahun 1978 kompleks makam itu menjadi suatu Taman Waruga. Oleh pemerintah taman waruga ini kemudian dijadikan sebagai benda cagar budaya dan sekaligus juga sebagai obyek wisata budaya yang unik dan menarik. Kompleks makam waruga Sawangan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Dr Daoed Joeseof pada tanggal 23 Oktober 1978.
Sejak abad ke-19, hingga kini masyarakat tidak lagi melihat ritual pemindahan waruga.
Menurut Pangkerego, ritual yang digelar tahun ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung para ‘tua-tua kampung’ memindahkan waruga. Lebih dari itu, masyarakat juga bisa melihat apa saja isi dalam waruga.
Proses ritual pemindahan waruga digelar selama tiga hari berturut-turut, dikerjakan Tim 9 bersama dengan 40 petugas yang ditunjuk khusus melalui upacara adat, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Waruga Kina Angkoan sebagai objek wisata budaya Minahasa Utara.
“Dana pemugaran dibiayai langsung pihak balai sungai dan nanti akan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Kedepan, pemerintah daerah akan lebih mengembangkan pariwisata di Minahasa Utara. Dan kami sudah memiliki layout pembangunan taman waruga, baik nama-nama para Dotu, jarak waruga hingga arah waruga itu, semua sudah diatur dengan baik,” kata Pangkerego seraya menhgarapkan, pada kunjungan kerja ke Sulut, 28 Desember 2016, Presiden Joko Widodo bisa meresmikan objek wisata waruga tersebut.

Sementara Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado Rusli Manorek mendukung pemerintah daerah dalam upaya perlindungan kebudayaan untuk mencegah dari kepunahan, kerusakan, tindak pencurian, atau hilangnya tradisi budaya itu sendiri.
“Perlindungan sekarang sudah dilakukan, kedepan pengembangan bagaimana? Apakah ini akan jadi desa adat atau bagaimana? Kalau jadi desa adat, maka kami sangat mendukung. Relokasi waruga ini akan saya laporkan juga kepada Dirjen Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Manorek.
Tentunya hasil yang baik dari segala usaha ini sedang dinanti publik. Masih dalam bayangan, wisatawan kedepan dapat menikmati megahnya Bendungan Kuwil Kawangkoan yang menjadi tanggul terakhir menapung debit air wilayah pengunungan Minahasa sehingga tidak terjadi banjir bandang di Kota Manado.
Disamping Bendungan Kuwil Kawangkoan, wisatawan bisa melihat makam keramat leluhur Tou Minahasa di Waruga Kina Angkoan. Kita berharap, objek wisata ini bisa menjadi satu dari sekian banyak destinasi unggulan di Provinsi Sulawesi Utara, yang dapat menjaga sejarah Minahasa serta mensejahterahkan masyarakat Minahasa Utara. Semoga.(findamuhtar)